
Advokat & Praktisi Kekayaan Intelektual Dr Ichwan Anggawirya, SSn, SH, MH. Foto: Dokumentasi pribadi.
Oleh Dr Ichwan Anggawirya, SSn, SH, MH,
Advokat & Praktisi Kekayaan Intelektual
UKMDANBURSA.COM – Di tengah masyarakat awam, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kerap dipahami sebagai akhir dari seluruh upaya hukum. Akibatnya, ketika suatu merek telah dibatalkan secara inkracht, seolah-olah tidak ada lagi ruang hukum bagi pemilik merek tersebut untuk memperjuangkan haknya.
Dalam praktik sengketa pembatalan merek produk, termasuk suatu produk minyak balur, persepsi tersebut kerap diperkuat oleh cara alat bukti historis diperlakukan seolah-olah telah final dan tak dapat diganggu gugat. Pemahaman ini tidak sepenuhnya tepat, karena hukum tidak pernah dimaksudkan untuk melindungi putusan yang lahir apabila terdapat kebohongan.
Ketika suatu putusan inkracht ternyata berdiri di atas alat bukti palsu, maka yang dipersoalkan bukan semata hasil akhir perkara, melainkan integritas proses pembuktian yang dijalankan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
Artikel pilihan:
Tuduhkan Kerry Hilangkan Kepemilikan Aset dalam Perjanjian dengan Pertamina Keliru
Alat Bukti Informasi Elektronik
Dalam perkara pembatalan merek, hakim menilai berbagai alat bukti untuk menentukan apakah suatu merek telah digunakan lebih dahulu, apakah terdapat itikad tidak baik, serta apakah pembatalan patut dilakukan. Di antara alat bukti tersebut, bukti surat dan dokumen termasuk informasi elektronik sering kali menjadi alat bukti yang bersifat menentukan (decisive evidence).
Masalah serius akan muncul apabila di kemudian hari terungkap bahwa alat bukti yang bersifat krusial tersebut tidak mencerminkan keadaan faktual yang sebenarnya, sehingga pada saat pemeriksaan perkara, alat bukti tersebut dinilai dan dipertimbangkan dalam asumsi keabsahannya. Dalam kondisi demikian, persoalan hukumnya tidak lagi berkutat pada siapa yang menang atau kalah, melainkan pada pertanyaan mendasar: apakah putusan pengadilan yang dibangun di atas fakta yang belakangan terbukti keliru masih dapat dipertahankan secara hukum?
Artikel pilihan:
Didakwa Korupsi Importasi Gula Mentah, Inilah Pledoi Lengkap Tom Lembong

Inkracht Bukan Perisai Kecurangan
Hukum mengenal asas universal fraus omnia corrumpit, yaitu kecurangan merusak seluruh bangunan hukum. Asas ini menegaskan bahwa putusan yang lahir dari tipu daya atau kebohongan tidak layak dilindungi oleh asas kepastian hukum. Kepastian hukum tidak dimaksudkan untuk mengabadikan hasil manipulasi, terlebih ketika manipulasi tersebut memengaruhi keyakinan hakim. Dengan kata lain, inkracht bukanlah perisai bagi perbuatan curang.
Dalam konteks perkara pembatalan merek, rawan terdapat sejumlah praktik yang berpotensi mengaburkan fakta dan karenanya patut dicermati secara serius:
1.Rekayasa Media Sosial sebagai Alat Bukti Palsu.
Dalam perkara pembatalan merek, misalnya ketika penggugat mengajukan bukti berupa informasi media sosial untuk membangun narasi bahwa suatu merek telah digunakan sejak tahun 2012, persoalan hukum muncul apabila di kemudian hari terbukti bahwa akun media sosial tersebut sebenarnya diedit atau dimodifikasi pada tahun 2024. Rekayasa tersebut dilakukan sedemikian rupa untuk menciptakan kesan historis palsu, seolah-olah penggunaan merek telah berlangsung sejak tahun 2012. Apabila unggahan hasil rekayasa tersebut kemudian diajukan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara, kondisi demikian berpotensi menciptakan ilusi prior use yang secara faktual tidak pernah ada.
Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi berfungsi sebagai alat bukti, melainkan sebagai alat untuk menyesatkan hakim. Informasi elektronik memang dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun sama sekali tidak kebal terhadap uji keabsahan. Keabsahan alat bukti elektronik bergantung pada keaslian data, integritas sistem, serta ketepatan kronologi waktunya.
Media sosial merupakan ruang digital yang sangat rentan direkayasa. Tangkapan layar, narasi visual, maupun tanggal unggahan tidak boleh diterima secara mentah, terlebih apabila digunakan untuk membuktikan fakta waktu yang menentukan nasib suatu merek.
Ketika informasi elektronik disusun secara sadar untuk menciptakan realitas palsu, maka yang terjadi bukan sekadar sengketa merek, melainkan rekayasa fakta dalam proses peradilan. Apabila pembatalan merek diputus berdasarkan alat bukti yang ternyata palsu, maka putusan tersebut mengandung cacat substansial.
Dalam kondisi demikian, putusan hakim secara objektif mengandung error in facto, karena pertimbangan hukumnya dibangun di atas fakta yang kemudian terbukti tidak benar. Cacat ini bersifat mendasar, bukan sekadar kesalahan prosedural.
Dari perspektif hukum pidana, apabila rekayasa dilakukan melalui pengeditan unggahan media sosial, manipulasi konten digital, atau rekayasa kronologi waktu dengan tujuan agar data tersebut dianggap autentik secara historis dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka perbuatan tersebut masuk dalam rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 35 UU ITE. Pasal ini mengatur perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, atau rekayasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang autentik, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE.
2.Pemalsuan Surat atau Dokumen Konvensional.
Apabila kecurangan dilakukan melalui pemalsuan surat atau dokumen konvensional, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP untuk pemalsuan yang diperberat, serta Pasal 266 KUHP terkait dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dalam KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023), substansi delik ini tetap dipertahankan dalam Pasal 391 sampai dengan Pasal 394, dengan penyesuaian sistematika dan penomoran.
Pemalsuan alat bukti dalam perkara pembatalan merek tidak berhenti pada ranah perdata semata. Hukum pidana membedakan kualifikasi pertanggungjawaban berdasarkan bentuk dan medianya, baik melalui dokumen konvensional maupun informasi elektronik.
Di sisi lain, dari perspektif perdata, pihak yang menggunakan alat bukti palsu untuk memenangkan gugatan pembatalan merek juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini karena penggunaan alat bukti palsu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melanggar asas itikad baik, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain melalui penyalahgunaan proses peradilan (abuse of process).
Dalam kondisi di mana suatu merek telah telanjur dibatalkan berdasarkan alat bukti yang kemudian terbukti palsu, hukum menyediakan mekanisme korektif berupa Peninjauan Kembali (PK). Inkracht tidak boleh menjadi alat untuk mengunci ketidakadilan.
Bukan Kekebalan Hukum, Tapi Keadilan
Putusan inkracht memang memberikan kepastian hukum, tetapi bukan kekebalan hukum. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang patut dipertahankan apabila ia lahir dari pemalsuan, baik melalui surat konvensional maupun melalui rekayasa informasi elektronik.
Ketika suatu merek dibatalkan berdasarkan bukti media sosial atau alat bukti lain yang direkayasa untuk menciptakan ilusi penggunaan sejak tahun tertentu, maka yang dipersoalkan bukan semata hak atas merek, melainkan keadilan itu sendiri. Dalam negara hukum, kemenangan yang diperoleh melalui kebohongan bukanlah kemenangan yang sah. ***



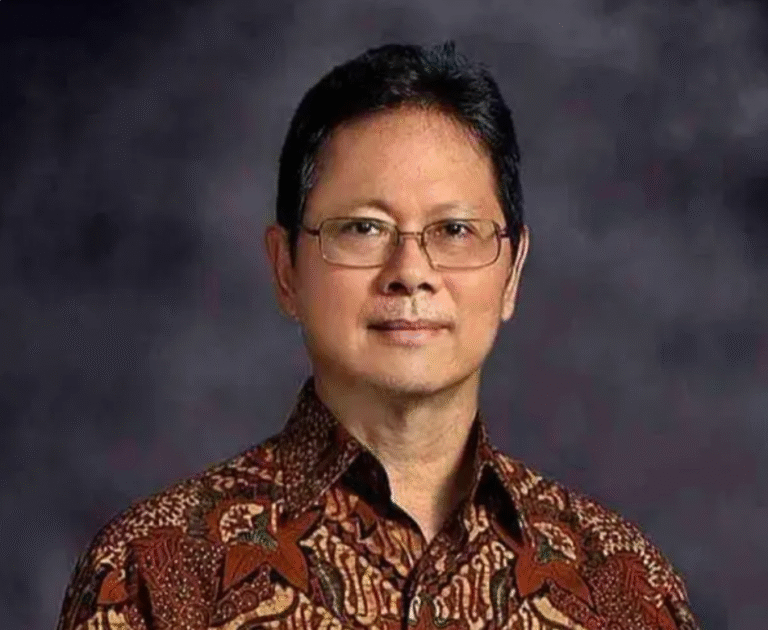

3 thoughts on “Putusan Inkracht Perkara Merek Produk Minyak Balur, Akhir atau Babak Baru?”